Pendahuluan
Term Aswaja (ahli sunnah wal jama’ah) muncul sebagai reaksi
daripada aliran Mu’tazilah yang telah berkembang sebelumnya. Seperti yang kita
ketahui bahwa aliran Mu’tazilah pernah menjadi mazhab resmi negara pada tahun
827 M oleh kalifah Abbasiyah yang bernama al-Ma’mun. Pada saat ini terjadi
peristiwa mihnah atau inquisition. Pemuka-pemuka
agama yang tidak mengakui al-Qur’an adalah makhluk akan ditangkap bahkan
disiksa.
Sekilas Pandang Asy’ariyah
Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Isma‘īl al-Asy‘arī lahir di Bashrah pada 260 H /
873 M dan meninggal pada 324 H/ 935 M. Dia adalah murid dari seorang tokoh
Mu’tazilah yang bernama al-Jubba’ī. Terkadang ketika ada perdebatan, al-Jubba’ī
diwakilkan oleh al-Asy’arī. Sebelum akhirnya membuat aliran sendiri, al-Asy’arī
mengikut paham Mu’tazilah selama 40 tahun.
Sebab yang menceritakan ke luarnya al-Asy’arī
dari aliran yang sudah dipercayainya selama 40 tahun adalah ketika dia bermimpi
bertemu Rasulullah saw. Dalam mimpinya Rasulullah mengatakan bahwa pemikiran
Mu’tazilah adalah salah dan menyuruh al-Asy’arī untuk membela sunnahnya.
Adapula sebab lainnya dikarenakan diskusinya dengan al-Jubba’ī.
Setelah bermimpi bertemu dengan Rasulullah saw, al-Asy’arī lalu berdiam di
rumahnya selama 15 hari untuk merenungkan pemikiran-pemikiran Mu’tazilah.
Kemudian dia ke luar menemui masyarakat dan
mengundang mereka untuk berkumpul. Selanjutnya, pada suatu hari Jum’at di Bashrah ia naik mimbar dan berkata,”Barang siapa yang telah
mengenalku, maka sebenarnya dia telah mengenalku. Dan barang siapa yang belum mengenalku, maka kini
saya memperkenalkan diri. Saya adalah fulan ibnu fulan. Saya pernah
mengatakan bahwa Alquran adalah makhluk, bahwa Allah tidak terlihat oleh indra
penglihatan kelak pada hari kiamat, dan abhwa perbuatan-perbuatan saya yang tidak
baik, saya sendirilah yang melakukannya. Kini saya bertobat dari pendapat
seperti itu, serta siap sedia untuk menolak pendapat Mu’tazilah, dan mengungkap
kelemahan mereka. Selama beberapa hari ini saya telah menghilang dari hadapan anda
sekalian, karena saya sedang berpikir. Menurut pendapat saya, dalil-dalil kedua
kelompok itu seimbang. Kemudian saya memohon petunjuk kepada Allah, maka
Allah memberikan petunjuk kepada saya untuk meyakini apa yang tertera dalam
kitab-kitab saya. Saya akan melepaskan apa yang pernah saya percayai, sebagaimana saya menanggalkan baju ini.
Doktrin Teologi al-Asy’arīyah
Sebagaimana aliran-aliran lainnya, setiap aliran memiliki doktrinnya
masing-masing. Begitu juga dengan al-Asy’arīyah, di antara
doktrin-doktrin tersebut antara lain sebagai berikut:
Akal dan Wahyu
Pada dasarnya golongan Asy’ary dan Mu’tazilah mengakui pentingnya
akal dan wahyu.34 Namun mereka berbeda pendapat dalam menghadapi persoalan yang memperoleh penjelasan
kontradiktif dari akal dan wahyu. Al-Asy’ari mengutamakan wahyu sementara Mu’tazilah
mengutamakan akal. Mu’tazilah memandang bahwa mengetahui Tuhan, kewajiban
mengetahui Tuhan, mengetahui baik dan buruk, kewajiban mengerjakan yang baik
dan menjauhi yang buruk adalah dapat diketahui lewat akal tanpa membutuhkan
wahyu.
Sementara dalam pandangan
al-Asy’arīyah semua kewajiban agama manusia hanya dapat diketahui melalui
informasi wahyu. Akal menurut al-Asya’ariyah tidak mampu menjadikan sesuatu menjadi
wajib dan tak dapat mengetahui bahwa mengerjakan yang baik dan menjauhi yang buruk adalah wajib bagi
manusia. Wajib mengenal Allah ditetapkan melalui wahyu hanyalah sebagai alat
untuk mengenal, sedangkan yang mewajibkan mengenal Allah ditetapkan melalui
wahyu. Bahkan dengan wahyu pulalah untuk dapat mengetahui ganjaran kebaikan
dari Tuhan bagi yang berbuat ketaatan, serta ganjaran keburukan bagi yang tidak melakukan ketaatan.
Iman dan Kufur
Al-Asy’arīyah dalam memandang iman setidaknya ada dua
pendapat. Hal ini disebabkan karena dalam aliran Murji’ah terbagi kepada dua
golongan, yaitu ekstrem dan moderat. Golongan ektstrem berpendapat bahwa iman
cukup dalam hati saja. Perihal perbuatan sekalipun mengarah kepada perbuatan
syirik (polytheis) itu sama sekali tidak mengganggu keimanan seseorang.
Iman
adalah tashdiq bi Allah, membenarkan adanya rasul-rasul serta
berita-berita yang dibawa para rasul. Konsekuensi dari tashdiq bi Allah adalah
dibuktikan dengan perkataan serta diaplikasikan dengan perbuatan. Sehingga
menurut penulis, iman tak cukup jika hanya ada di hati saja. Melainkan butuh
yang namanya pembuktian melalui lisan dan perbuatan.
Kufur
adalah lawan dari kata iman. Berarti kufur adalah ingkar, tidak percaya. Dalam
kaitan dengan pembahasan ini, nanti akan dijelaskan di pembahasan selanjutnya.
Ringkasnya, al-Asy’arīyah tidak mudah mengkafirkan orang lain.
Kedudukan Pelaku Dosa
Orang mukmin yang melakukan dosa besar
masih dipandang sebagai mukmin. Karena adab golongan al-Asy’arīyah lebih kepada menyerahkan urusan ini
kepada Tuhan. Masalah ini pertama kali timbul ketika peristiwa taḥkim.
Keadilan Tuhan
Lagi-lagi al-Asy’arīyah berbeda pendapat dengan Mu’tazilah.
Kedua aliran ini memang sering berbeda dalam banyak hal terkait teologi.
Mu’tazilah mengharuskan bahwa Allah harus adil. Allah harus menyiksa yang salah
dan memberi pahalla kepada orang yang berbuat baik. Ya, salah satu uṣūl
al-khamsah Mu’tazilah ada tentang keadilan. Menurut al-Asy’arīyah Allah tidak memiliki suatu keharusan
apapun, karena Allah ada penguasa mutlak. Semua yang Allah lakukan adalah adil.
Kebebasan Berkehendak
Menurut al-Asy’arīyah, manusia adalah lemah. Bergantung
kepada Allah. Al-Asy’arīyah lebih dekat kepada paham Jabariyah.
Zat dan Sifat Allah
Zat dan sifat Allah adalah salah satu
persoalan yang dibicarakan dalam ilmu teologi. Aliran-aliran teologi dalam hal
ini terbagi kepada aliran yang percaya Allah memiliki sifat dan aliran yang
tidak memercayai bahwa Allah memiliki sifat. Karena jika Allah memiliki sifat,
maka akan ada sesuatu yang qadim selain Allah. Hal ini menimbulkan suatu
pernyataan bahwa ada dua Tuhan.
Persoalan-persoalan
teologi banyak dimunculkan oleh kalangan Mu’tazilah, termasuk tentang zat dan
sifat Allah. Mu’tazilah menganut pancasila (uṣūl al-khamsah), yaitu
salah satunya tauhid. Allah adalah zat yang maha tunggal. Tidak ada yang qadim
melainkan Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini Mu’tazilah menolak bahwa Tuhan
memiliki sifat.
Al-Asy’arīyah dalam hal
ini berlawanan dengan Mu’tazilah, karena al-Asy’arīyah berpendapat bahwa Allah memiliki sifat.
Bagaimana sifat Allah tidak diketahui caranya dan batasnya. Sifat yang
disebutkan dalam pembahasan ini tidak terbatas pada sifat semisalnya penyayang,
pengasih, atau selainnya. Akan tetapi sifat di sini juga berarti Tuhan
memiliki jasmani (anthropomorphisme), seperti Allah memilik wajah,
tangan, mata, dan seterusnya. Sehingga konsekuensi yang ditimbulkan nanti bahwa
Allah dapat dilihat di hari kemudian.
Melihat Tuhan
Karena Mu’tazilah menolak Allah memiliki
sifat, maka mereka menolak bahwa Allah dapat dilihat di hari kemudian. Sangat
berbeda dengan al-Asy’arīyah yang berpendapat bahwa Allah dapat
dilihat nanti di hari kemudian.
Al-Qur’an adalah Qadim
Pemikiran kalam al-Asy’ari tentang Kalam Allah (al-Qur’an) ini
dibedakannya menjadi dua, Kalam Nafsi yakni firman Allah yang bersifat
abstrak tidak berbentuk yang ada pada Zat (Diri) Tuhan,
Ia bersifat Qadim dan Azali serta tidak berubah oleh adanya perubahan ruang, waktu dan
tempat. Maka al-Qur’an sebagai kalam Tuhan dalam artian ini bukanlah
makhluk.
Sedangkan kalam Lafzi adalah
kalam Allah yang diturunkan kepada para Rasul yang dalam bentuk huruf atau
kata-kata yang dapat ditulis, dibaca atau disuarakan oleh makhluk-Nya, yakni
berupa al-Qur’an yang dapat dibaca sehari-hari. Maka kalam dalam artian ini bersifat
hadis (baru) dan termasuk makhluk.





![Muhammad 'Abduh dan Ide Pembaharuan [Part 1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSRjL-qXuhy01mZpPv8ZFo_n0mOhgJpraVon-DhfV0lV2moRebknbkOdX_tl2xvTlmLoGXXM3_OmE3YQsaAKvjW8MCmyb-nQ6LpxWTD_M6CTkzMlyHKfC7240Lreu9nkParJ8c_LGTle0g/w680/%2527Abduh+uplot.jpg)




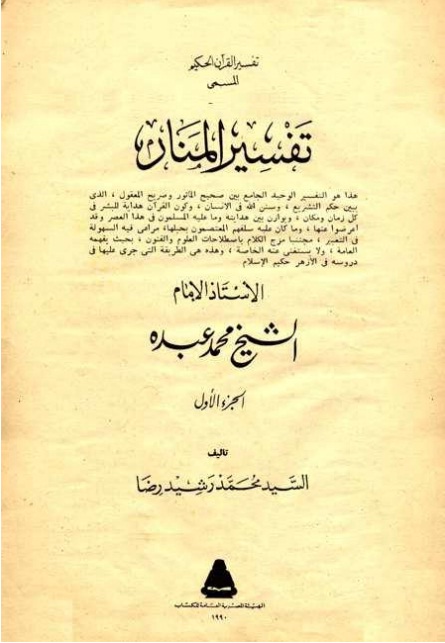

0 Comments