Tafsir al Bayani li al-Qur’an al Karim
Pendahuluan
Ā’ishaBinti al-Shāthi merupakan mufassir
perempuan pertama pada masanya, ia meneliti banyak ayat al-Quran secara bayani
sehingga penafsirannya itu menghadirkan suasana baru dalam bidang tafsir
al-Quran dimasa modern ini namun ia juga tidak menyimpang dari penafisran
klasik, sehingga dapat diterima oleh para pembacanya. Disini pemakalah akan
menguraikan pembahasan mengenai ‘Ā’isha Binti al Shāthi’.
Biografi ‘Ā’isha Binti al
Shāthi’
Nama Binti al-Shāthi‟ adalah Ā’isha„Abd al-Raḥmān. Seorang guru besar sastra dan
bahasa
Arab di Universitas „Ain al-Syams, Mesir. Juga menjadi guru besar tamu di
Universitas Umm Durman, Sudan, serta guru besar tamu di Universitas Qarawiyyin,
Maroko. Bint al-Syāthi. Lahir di Dimyāt, sebelah barat Delta Nil, tanggal 6 November 1913.
Bint
al-Syāthi‟ lahir di tengah-tengah keluarga muslim yang saleh. Ayahnya, Abd
al-Raḥmān, adalah tokoh sufi dan guru teologi di Dimyāt. Pendidikan Bint
al-Syāthi‟ dimulai ketika
berumur lima tahun, yaitu dengan belajar membaca dan menulis Arab pada syaikh
Mursi di Shubra Bakhum, tempat asal ayahnya. Selanjutnya, ia masuk sekolah
dasar untuk belajar gramatika bahasa Arab dan dasar-dasar kepercayaan Islam, di
Dimyāt. Setelah menjalani pendidikan lanjutan, pada 1939 ia
berhasil meraih jenjang Licence (Lc) jurusan sastra dan bahasa Arab, di
Universitas Fuad I, Kairo. Dua tahun kemudian Ā’ishaBinti al-Shāthi
menyelesaikan jenjang Master, dan pada 1950 meraih gelar doktor pada bidang
serta lembaga yang sama pula, dengan disertasi berjudul al-Gufran li Abu al-A‟la al-Ma‟ari. 46 Minatnya terhadap kajian
Tafsir dimulai sejak pertemuannya dengan prof. Amin alKhulli, seorang pakar
tafsir yang kemudian menjadi suaminya, ketika ia bekerja di Universitas Kairo.
Kemudian Ā’ishaBinti al-Shāthi
mendalami tafsirnya yang terkenal, al-Tafsir alBayani li al-Qur‟an al-Karim I, yang diterbitkan pada 1962. Bahkan
dapat dikatakan bahwa
Ā’ishaBinti al-Shāthi adalah satu-satunya Mufassir al-Quran dari kalangan
wanita. Karyakarya Ā’ishaBinti al-Shāthi lainnya tentang tafsir antara lain
Kitabina al-akbar (1967); tafsir al-Bayani li al-Qur‟an al-Karim (1969); Maqal fi al-Insan Dirasah
Qur‟aniyyah (1969); alQur‟an wa al-Tafsir al-‟Asyri (1970); Al-I‟jaz al-Bayani li al-Qur‟an (1971); asy-Syakhshiyyah al-Islamiyyah Dirasah
al-Qur‟aniyyah (1973).
Metode Penafsiran
Ā’ishaBinti al-Shāthi
berkeyakinan bahwa: pertama, al-Qur‟an menjelaskan
dirinya dengan dirinya sendiri (al-Qur‟an yufassiru ba‟dhuhu ba‟dh)47; kedua, al-Qur‟an harus dipelajari dan dipahami keseluruhannya sebagai suatu
kesatuan dengan karakteristik-karakteristik ungkapan dan gaya bahasa yang khas,
dan ketiga, penerimaan atas tatanan kronologis al-Qur‟an dapat memberikan keterangan sejarah mengenai kandungan al-Qur‟an tanpa
menghilangkan keabadian nilainya.
Berdasarkan tiga diktum atau
basis pemikiran di atas, Ā’ishaBinti al-Shāthi mengajukan metode tafsirnya,
sebuah metode untuk memahami al-Qur‟an secara obyektif.
Menurutnya, metode ini diambil dan dikembangkan dari prinsip-prinsip metode
penafsiran Amin al-Khulli (1895-1966) yang terdiri dari empat langkah:
1.
Basis metodenya adalah
memperlakukan apa yang ingin dipahami dari Al-Qur‟an secara objektif, yang dimulai dengan pengumpulan semua surah
dan ayat mengenai topik yang ingin dipelajari. Pengumpulan satu tema dari
keseluruhan ayat ini tidak berarti mengingkari kenyataan bahwa al-Qur‟an turun dalam tenggang waktu yang lama, yang gaya ungkapannya
bisa berbeda antara waktu-waktu pertama dengan berikutnya. Sebab, kenyataan
inilah satu-satunya cara yang paling memadai untuk menangkap makna al-Qur‟an.
2.
Surat dan ayat tersebut
kemudian disusun sesuai dengan kronologi pewahyuannya sehingga keterangan
mengenai wahyu dan tempatnya (asbab al-nuzul) dapat diketahui. Namun asbab
nuzul di sini tidak dipandang sebagai penyebab turunnya ayat melainkan hanya
sebagai keterangan kontekstual yang berkaitan dengan pewahyuan suatu ayat. Yang
harus diperhatikan di sini adalah generalitas kata yang digunakan bukan
kekhususan peristiwa pewahyuannya (al-‘ibrah bi „umum al-lafz la bikhusus
al-sabab). Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hasil
metode ini akan dikacaukan oleh perdebatan ulama tentang asbab annuzul.
Pentingnya pewahyuan terletak pada generalitas kata-kata yang digunakan, bukan
pada kekhususan peristiwa pewahyuannya.
3.
Untuk memahami petunjuk
lafaz, karena al-Qur‟an menggunakan
bahasa Arab, maka harus dicari petunjuk dalam bahasa aslinya yang memberikan
rasa kebahasaan bagi lafaz-lafaz yang digunakan secara berbeda, kemudian
disimpulkan petunjuknya dengan meneliti segala bentuk lafaz yang ada di
dalamnya, dan dengan dicarikan konteksnya yang khusus dan umum dalam ayat
al-Qur‟an secara keseluruhan. Di
sini digunakan “analisa bahasa” (semantik).
1. 4.
Untuk memahami pernyataan-pernyataan yang sulit, seorang mufasir harus
berpegang pada makna nash dan semangatnya (maqasid asy-syari‟), kemudian dikonfrontasikan dengan pendapat yang sejalan dengan
maksud teks yang bisa diterima sedangkan penafsiran yang berbau sektarian dan
israiliyyat bisa dijauhkan. Menurut Ā’ishaBinti al-Shāthi, metodenya
dimaksudkan untuk mendobrak metode klasik yang menafsirkan al-Qur‟an secara tartil, dari ayat ke ayat secara berurutan, karena
metode klasik ini setidaknya mengandung dua kelemahan: pertama, memperlakukan
ayat secara individual yang terlepas dari konteks umumnya sebagai kesatuan,
padahal al-Qur‟an adalah satu kesatuan yang
utuh, di mana ayat dan surat yang satu dengan yang lainnya saling terkait, dan;
kedua, kemungkinan masuknya ide mufasir sendiri yang tidak sesuai dengan maksud
ayat yang sebenarnya. 49 Kritik Ā’ishaBinti al Sh
āthi‟ terhadap metode tafsir
klasik ini bukan tidak beralasan. Kenyataannya, setelah tafsir al-Tabari,
kitab-kitab tafsir senantiasa memiliki corak tertentu yang bisa dirasakan
secara jelas bahwa penulisannya “memaksakan sesuatu pada al-Qur‟an”, bisa berupa paham akidah, fiqh, tasawuf, atau setidaknya
aliran kaidah bahasa tertentu. Hal ini bisa
dilihat, misalnya pada tafsir al-Kasysyaf, karya
Az-Zamakhsyari (1074-1143), Anwar al-Tanzil karya al-Baidhawi (w. 1388), atau
Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan (1344). Dengan metode ini, Ā’ishaBinti al-Shāthi
sengaja mematok aturan-aturan yang ketat, agar al-Qur‟an benar-benar berbicara tentang dirinya sendiri tanpa campur
tangan mufasir, dan dipahami secara langsung sebagaimana oleh para sahabat.
Karena itu rujukan-rujukan seperti yang terkait dengan asbab nuzul hanya
dipahami sebagai data sejarah, sehingga apa yang dimaksud Tuhan dalam suatu
pewahyuan benar-benar pesan yang melampaui peristiwa tertentu. Karena itu pula,
pandangan-pandangan para mufasir sebelumnya, terutama al-Tabari (w. 923),
al-Zamakhsyari (w. 1144), Fakhr al-Din al-Razi (w. 1210), Isfahani, Nizam
al-Din al-Nisaburi, Abu Hayyan al-Andalusi (w. 1344), Ibn Qayyim al-Jauziyyah,
al-Suyuthi dan Abduh (w. 1905) yang sering dikutip Ā’ishaBinti al-Shāthi dalam
tafsirnya, bukan dijadikan rujukan melainkan justru sering menunjukkan
kekeliruannya dan alasannya yang terlalu di buat-buat, karena tidak sesuai
dengan maksud al-Qur‟an sebagaimana yang
dipahami lewat metode yang dikembangkan.
Corak Penafsiran
Corak yang digunakan dalam tafsir ini yakni corak
adabi. Ā’ishaBinti al-Shāthi dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan metode
analisa bahasa & munasabah antar ayat dan surat.
Ā’ishaBinti al-Shāthi menafsirkan dengan corak adaby atau yang belakangan
popular dengan istilah bayani. Istilah bayani ini tidak menjadi sebuah
perspektif baru mengingat bahwa selama ini pemahaman kebahasaan, baik
stilistika dan gramatikal bahasa dalam Tafsir cenderung mengadopsi pendapat
sebelumnya. Padahal ini merupakan area yang sangat potensial dalam upaya
memahami al-Qur‟an secara integral, sistemik
dan relevan dengan kondisi citarasa keArab-an.
Sumber Penafsiran
Ā’ishaBinti al-Shāthi menafsirkan ayat al-Quran
melalui tafsir bil-ma‟tsur karena beliau
tidak ingin mengkorelasikan antara sesuatu yang rancu menjadi sempurna, karena
ia ingin al-Quran berbicara dengan sendirinya tanpa argument-argumen yang
kurang jelas dipahami.
Sebab penafsirannya merupakan corak tafsir modern yang menganut madzhab dan
aliran tematik umum (mauḍūi „ām). Pengkajian sastra tematik Ā’ishaBinti al-Shāthi dihususkan pada
pembahasan sastra bahasa dalam satu surat, beliau tidak mengambil seluruh surat
dalam al-Quran akan tetapi beberapa surat pendek saja yang terdapat pada juz
„Āmmā, yaitu : 1. Dalam buku pertamanya beliau menafsirkan 7 (tujuh) surat,
diantaranya: aḍ-Ḍuhā, as-Syārẖ, az-Zalzalah, al-Ādiyāt, an-Nāzi‟āt, al-Balad, dan at-Takātsur.
2. Dan buku keduanya beliau menafsirkan 7 (tujuh) ayat juga diantaranya : al-„Ālaq,
al-Lail, alFajr, al-Humazah, dan al-Mā‟ūn.
Karakteristik Penafsiran
Diantara karakteristik Tafsir Ā’ishaBinti al-Shāthi
ialah:
1. Mengungkap
makna-makna dibalik sinonim kata ‘
2. Mengungkap
kemukjizatan jumlah pengulangan kata dalam al-Qur‟an
3. Memaknai
sumpah dengan perspektif yang baru yakni muqsam bih sebagai pengalihan dan
bukan pengagungan
4. Mengungkap
munasabah antara ayat dan surat dan mengaitkannya satu sama lain terutama dari
sudut pandang kebahasaan, dan dalam penafsirannya dari segi bahasa dan satra
membuat dia menonjol dan unggul dari penafsiran yang lainnya.
Selain karakteristik diatas,
Tafsir Ā’ishaBinti al-Shāthi tidak luput dari empat prinsip penafsiran yakni:
1. Menafsirkan
Al-Qur‟an dengan Al-Qur‟an, yang berpegang pada prinsip al-Qur‟ân
yufassiru ba‟duhu ba‟dan, bahwa ayat-ayat al-Qur‟an menafsirkan sebagian lainnya.
2. Prinsip
munâsabah antar ayat maupun antar surat.
3. Ibrah
itu hanya memuat pada bunyi teks, bukan dengan asbâb an-Nuzûl (al-ibrah bi
„umûm al-lafdzi lâ bi khusûs al-sabab), kecuali untuk lafadz yang
menunjukkan khusus.
4. Prinsip
bahwa kata-kata dalam al-Qur‟an tidak ada sinonim.
Kritik
terhadap Metodologi ‘Ā’isha Binti al Shāthi’
Dari beberapa referensi penulis dapat
menguraikan bahwa metode Ā’ishaBinti al-Shāthi ini mempunyai beberapa
kelemahan, di antaranya:
1. Jika
pemahaman lafaz al-Qur‟an harus dikaji
lewat pemahaman bahasa Arab yang merupakan bahasa “induknya”, padahal
kenyataannya, tidak sedikit istilah dalam syair dan prosa Arab masa itu tidak
dipakai oleh al-Qur‟an, maka itu berarti
membuka peluang dan menggiring masuknya unsur-unsur asing ke dalam pemahaman
al-Qur‟an; sesuatu yang sangat
dihindari oleh Ā’ishaBinti al-Shāthi sendiri.
2.
Ā’ishaBinti al-Shāthi kurang
konsisten dengan metode penafsiran yang ditawarkan, mengkaji tema tertentu,
melainkan lebih pada analisis semantic. Kenyataannya, ketika „Ā‟isha
Binti al-Shāthi menafsirkan ayat-ayat pendek, ia mengumpulkan lafaz-lafaz yang
serupa dengan lafaz yang ditafsirkan, kemudian menganalisis dari sisi bahasa
(semantic).
3. Mengenai
penafsiran Ā’ishaBinti al-Shāthi beliau tidak terfokus dengan gendernya dan
bersifat netral.
Kesimpulan
Seorang mufasir dituntut berpengetahuan luas
dalam ilmu-ilmu bahasa Arab, seperti tata bahasa, retorika, dan gaya bahasa;
juga dalam ilmu-ilmu al-Quran, sebab-sebab pewahyuan, mengenai ayat-ayat yang
jelas (muhkamāt) dan ayat-ayat yang samar (mutasyābīhāt), dan
lain sebagainya. Ia juga harus berpengetahuan luas dalam ilmu-ilmu hadis,
teologi, hokum, heresiology (ilmu-ilmu tentang bid‟ah), dan sejarah Islam. Ia
juga tidak ingin terperangkap pada kesalahan mufasir masa lalu yang menerima Isrā`īliyyāt
dan materi-materi asing dari para Mu‟allaf, sehingga
mereka memasukkannya ke dalam tafsir mereka, apa yang sesungguhnya tidak
dimaksudkan oleh al-Qur‟ān sendiri. Demikian
juga ia menolak terlibat dalam pembahasan-pembahasan mendetail mengenai sejauh
mana ayat-ayat tertentu al-Quran sejalan dengan ilmu dan teknologi modern,
sebab hal ini menurutnya juga tidak pernah dimaksudkan oleh al-Quran. Ayat-ayat
tersebut, yang menjabarkan fenomena alam, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan,
aspek-aspek ruang angkasa serta hal-hal lain yang menakjubkan, tidak
dimaksudkan sebagai pelajaran pada berbagai ilmu modern yang berbeda-beda atau
sebagai bukti-bukti tekstual yang sejalan dengan teori-teori mutakhir di
berbagai lapangan pengetahuan empiric modern. Pandangan teologis mengenai
kebebasan berkehendak dan tanggung jawab manusia yang dikemukakan Ā’ishaBinti al-Shāthi
pada tafsirnya ini, didasari oleh pemahaman konstektual dan linguistiknya yang
ketat terhadap sebuah kata, sering diungkapkan dalam berbagai contoh lain
materi al-Quran.
Contoh
Penafsiran ‘Ā’isha Binti al Shāthi’
Ā’ishaBinti al-Shāthi telah mengajukan
pengamatan menarik lain dalam tafsir alQuranya, seperti mengeani sumpah-sumpah.
56 Signifikan sumpah negative lā uqsimu, fungsifungsi dari apa
yang disebut partikel tak berguna (otiose particle) bā‟ dalam kedudukannya sebagai predikat laysa dan mā.
Mungkin benar bahwa perhatian Ā’ishaBinti al-Shāthi lebih banyak diarahkan
kepada karakteristik-karakteristik sastra dalam al-Quran. Walaupun demikian,
itu karena metodenya mengonsentrasikan diri pada apa yang telah ada. 57 Salah satu contoh penafsiran Ā’ishaBinti al-Shāthi dengan
pendekatan sastra dapat dilihat bagaimana beliau menafsirkan surat al-Duha.
Menurut beliau surat Duha dimulai dengan qasam wawu. Pendapat yang berlaku
dikalangan ulama terdahulu mengatakan bahwa, sumpah al-Qur‟an ini mengandung makna pengagungan terhadap muqsam bih (obyek
yang digunakan untuk bersumpah). Gagasan ini berkembang luas, sehingga menyeret
mereka untuk melakukan pemaksaan di dalam menjelaskan segi keagungan pada
setiap hal yang digunakan al-Qur‟an untuk bersumpah
dengan wawu Qasam dengan wawu pada umumnya adalah gaya bahasa yang menjelaskan
makna-makna dengan penalaran inderawi.
Keagungan
yang tampak dimaksudkan untuk menciptakan daya tarik yang kuat. Sedangkan
pemilihan muqsam bih dilakukan dengan memperhatikan sifat yang sesuai dengan
keadaan. Menelusuri sumpah-sumpah al-Qur‟an seperti yang
terdapat dalam ayat al-Duha, kita menemukanya dikemukakan sebagai lafitah
(penarikan perhatian) terhadap suatu gambaran materi yang dapat diindera, dan
realitas yang dapat dilihat, sebagai inisiatif ilustratif bagi gambaran lain
yang maknawi dan sejenis, tidak dapat dilihat dan diindera. Muqsam bih didalam
dua surat al-Dhuhā adalah gambaran bersifat fisik dan realita konkret, yang
setiap hari dapat disaksikan manusia ketika cahaya memancar pada dini hari.
Kemudian turunnya malam ketika sunyi dan hening tanpa mengganggu system alam.
Silih bergantinya dua keadaan, dapat menimbulkan keingkaran, bahkan sebagai
suatu yang tak pernah telintas dalam pikiran siapapun.
Dengan demikian, al-Qur‟an dengan sumpah-sumpahnya dalam surat al-Duha menjelaskan
makna-makna petunjuk dan kebenaran, atau kesesatan dan kebatilan, dengan
materi-materi cahaya dan kegelapan. Penjelasan yang maknawi dengan yang hissi
ini dapat kita kemukakan pada sumpah-sumpah al-Qur‟an dengan wawu Yang demikian dapat diterima tanpa paksaan dalam
pentakwilan ayat-ayat. Untuk itu, Allah pun bersumpah, bahwa Dia mengisyaratkan
terangnya wahyu pada hati beliau pada mulanya seperti waktu dhuha menguatkan
kehidupan dan menumbuhkan tetumbuhan. Sesudah itu, seperti malam hari ketika
telah sunyi agar segala potensi beristirahat dan jiwa bersiap-siap untuk
menghadapi pekerjaan, sebagaimana dimaklumi pada awalnya Nabi SAW. menerima
wahyu dengan berat, sehingga keterlambatan wahyu adalah untuk memantapkan dan
menguatkan jiwa, guna memikul apa yang akan dihadapi. Sehingga sempurnalah
hikmah Allah Ta‟ala dalam mengutus beliau
kepada makhluk-nya.59 Para Mufassir berpendapat
mengenai surat ini diantaranya:
1. At-Thabari
memilih arti ad-Dhuhā ialah siang, sebab sinar mentari telah tampak, dan
memilih arti “malam ketika telah sunyi” dengan ketenangan bagi penghuninya.
2. Al-Zamakhsyari mengatakan bahwa waktu Dhuhā adalah permulaan siang ketika
matahari naik dan memancarkan sinarnya. Dikatakan juga bahwa yang dimaksudkan
dengan waktu dhuha adalah siang hari. Sementara itu dia mengartikan sajā dengan
“tenang dan tak bergerak kegelapannya” dan dapat dikatakan pula bahwa maknanya
adalah tenangnya manusia dan suara pada saat itu.
2. Menurut
Abu Hayyan: sajā al-lail, ketika malam mundur. Dan dikatakan pula ketika
dating, dan al-Farra‟ mengatakan “ketika
gelap dan tak bergerak kegelapannya.” Sedangkan ibn al-„Arabi mengatakan
“ketika gelapnya memuncak.”
3. Al-Naisaburi
membolehkan jika makna sajā adalah tenangnya manusia di dalamnya,
sehingga isnād (penyandaran) disini bersifat majāzi.
4. Muhammad
„Abduh mengatakan bahwa waktu Dhuhā adalah sinar matahari pada
permulaan siang. Dan “Sajā al-lail” menurut apresiasinya adalah
apa yang anda dapati berupa ketenangan penghuninya dan terputusnya kehidupan
dari gerakan didalamnya.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Suyuthi, Dur al-Mansur,
Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1313
Binti al-Shāthi, „Ā‟isha. Tafsir Bint al-Syathi, Kairo: Dar al-Ma‟arif, 1977
Binti al-Shāthi, „Ā‟isha. Tafsir Bint al-Syathi, terj. Muzakir, Bandung: Mizan, 1996
J. Boullata, Issa.
Tafsir al-Qur‟an Modern Studi atas
Metode Bint al-Syathi, dalam Jurnal Al-Hikmah, Oktober 1991
Mu‟in, Hamdani, disertasi: Metodologi tafsir Ā’ishaBinti al-Shāthi,
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008
Shihab, Quraish. Membumikan
al-Qur‟an. Bandung: Mizan,
1997
Syaiful Amin Ghafur, Profil
Mufassir Quran, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani



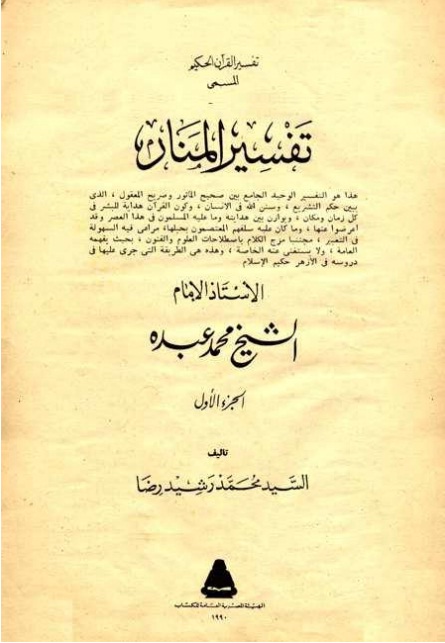




![Muhammad 'Abduh dan Ide Pembaharuan [Part 1]](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgSRjL-qXuhy01mZpPv8ZFo_n0mOhgJpraVon-DhfV0lV2moRebknbkOdX_tl2xvTlmLoGXXM3_OmE3YQsaAKvjW8MCmyb-nQ6LpxWTD_M6CTkzMlyHKfC7240Lreu9nkParJ8c_LGTle0g/w680/%2527Abduh+uplot.jpg)



0 Comments